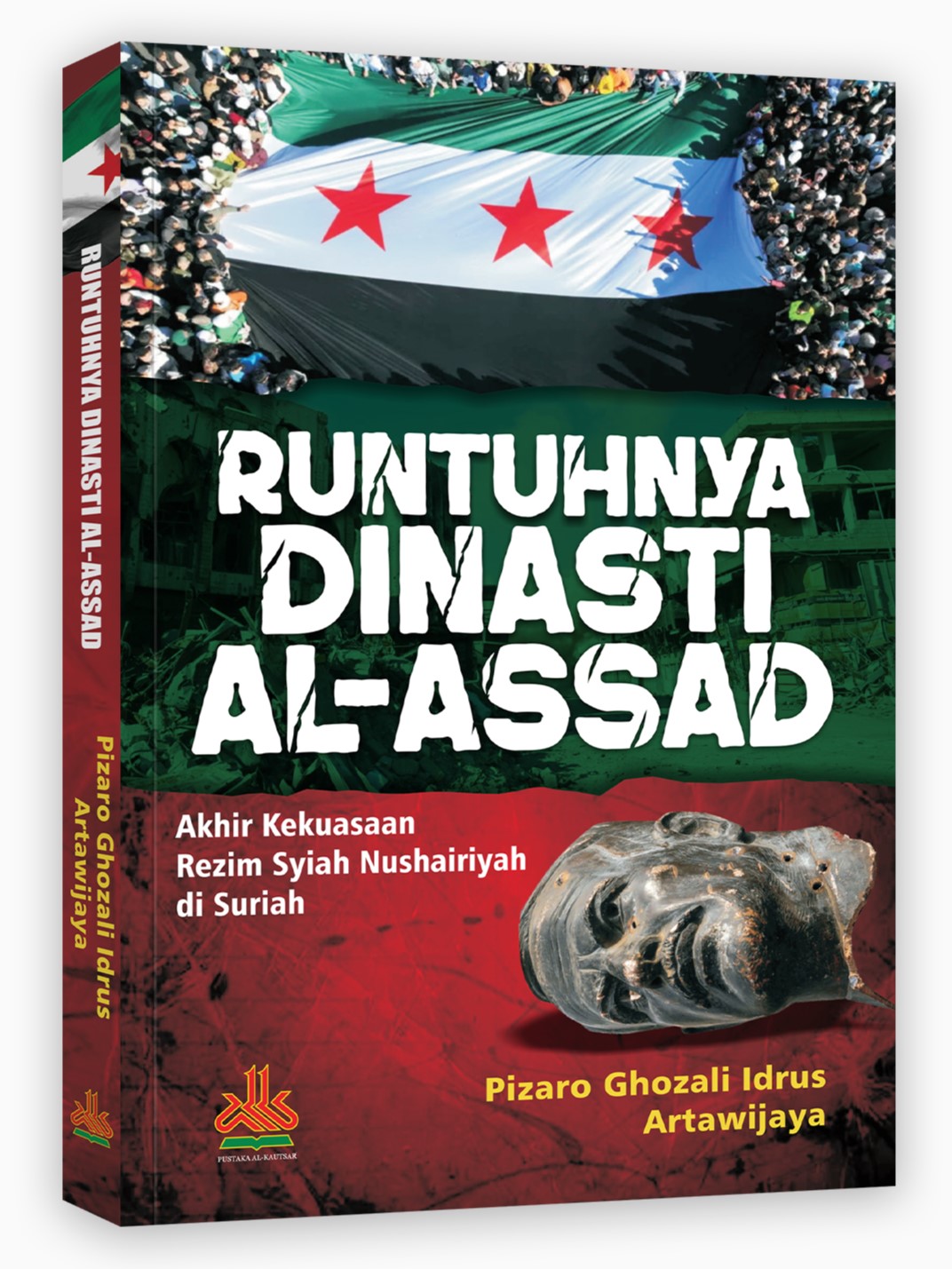Di jantung Kota Gaza, di sebuah kamp pengungsian darurat yang sarat penderitaan, perempuan muda Palestina bernama Rifqa Al-Daghl (23) menjalani hari-harinya dalam pertarungan sunyi.
Ia harus melawan realitas pahit yang ditinggalkan perang Israel sejak Oktober 2023.
Perang yang oleh berbagai laporan internasional disebut telah melampaui batas konflik konvensional hingga mendekati genosida itu menghancurkan rumah Rifqa dan merenggut nyawa suaminya.
Ia kini harus bertahan menghadapi dinginnya cuaca dan kelaparan bersama bayi perempuannya, Malak, di dalam sebuah tenda reyot yang didirikan tak jauh dari tempat pembuangan sampah.
Tenda itu terbuat dari kain-kain usang dan potongan plastik yang telah rapuh. Ia nyaris tak menyediakan perlindungan layak.
Angin kencang mengguncang sisinya setiap hari, seolah hendak mencabutnya dari tanah.
Sementara air hujan merembes masuk melalui celah-celah, menggenangi lantai tanah yang becek.
Rifqa, yang sebelum perang menjalani kehidupan sederhana namun tenang, kini duduk membungkuk di depan tungku darurat berbahan kayu bakar basah.
Ia berusaha menyiapkan minuman hangat untuk putrinya yang terus menempel di punggungnya, ketakutan oleh badai.
“Saya tak pernah membayangkan akan hidup dalam kondisi sekejam ini. Saya kehilangan rumah dan suami. Hidup tak lagi seperti dulu,” katanya lirih.
Sebelum perang pecah pada 8 Oktober 2023, Rifqa tinggal di rumah sederhana bersama suaminya, Yusuf Hassan (24), yang bekerja di sebuah pabrik roti dan kue.
Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, tetapi cukup untuk menghadirkan rasa aman dan kebahagiaan.
Mereka menikah hanya sepekan sebelum serangan Israel dimulai, menenun mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Namun mimpi itu segera runtuh.
Keduanya terpaksa mengungsi dari rumah mereka di Beit Lahia, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, sebagaimana dialami ratusan ribu warga Palestina lainnya.
Kelahiran putri mereka, Malak, pada November 2024 sempat menjadi secercah kebahagiaan di tengah kehancuran. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama.
Yusuf kehilangan pekerjaannya—satu-satunya sumber nafkah keluarga—di tengah kelaparan mematikan akibat kebijakan Israel yang menghambat masuknya bantuan secara teratur.
Tak menyerah pada keadaan, Yusuf pada 5 Agustus mendatangi area dekat perlintasan Zikim, di barat laut Gaza, untuk mendapatkan sekarung tepung dari truk bantuan.
Ratusan warga berdesakan di lokasi itu. Namun seorang penembak jitu Israel melepaskan tembakan. Yusuf gugur seketika.
Memasuki musim dingin, perjuangan Rifqa semakin berat. Ia berupaya menambal lubang-lubang tenda yang dihuni sembilan orang, melawan hujan dan angin yang terus menerpa.
Kamp pengungsian di dekat tempat pembuangan sampah itu dipenuhi tenda-tenda serupa, masing-masing menyimpan kisah luka dan kehilangan.
Sementara para pengungsi bergulat dengan dingin, kelaparan, dan penyakit.
Derita yang berlapis
Di tenda sebelah, Manal Al-Ar‘ir (52) menanggung penderitaan berlapis. Ia kehilangan suaminya, Ayman (50), pada 23 Desember 2023, saat sang suami berusaha menyelamatkan kerabat mereka di lingkungan Shuja’iyya, Gaza timur, yang dihantam serangan Israel.
Manal kini mengalami kelumpuhan.
“Suami saya pedagang logam. Kami hidup bahagia di rumah kami di Shuja’iyya,” katanya mengenang masa lalu.
Namun pada hari itu, Ayman bergegas menolong keluarganya setelah pemboman, dan tewas akibat rentetan serangan Israel.
Perang menghancurkan rumah mereka, memaksa Manal dan lima anaknya tinggal di sebuah tenda penuh serangga di dekat tempat sampah, kehilangan hampir segala-galanya.
Direktur Pusat Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Palestina, Zaher Al-Wahidi, mencatat bahwa perang pemusnahan di Gaza telah menewaskan 70.300 warga Palestina dan melukai sekitar 171.000 lainnya.
Di antara para korban terdapat 20.000 anak-anak, 10.000 perempuan, dan 5.000 lansia.
Perang yang sama telah menjadikan 22.750 perempuan sebagai janda dan 57.000 anak sebagai yatim—49.000 kehilangan ayah, 5.000 kehilangan ibu, dan 3.000 kehilangan kedua orang tuanya.
Sebanyak 2.600 keluarga musnah seluruh anggotanya, sementara 5.000 keluarga mengalami pembantaian dengan hanya satu anggota yang selamat. Sebanyak 6.000 keluarga lainnya kehilangan sebagian anggota.
“Angka-angka ini mengerikan. Ini mencerminkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Al-Wahidi.
Lebih dari seribu bayi berusia di bawah satu tahun tewas. Sebanyak 450 bayi lahir selama perang, namun meninggal di bawah bombardir.
Kehancuran infrastruktur memperparah krisis, memicu kelaparan dan merebaknya penyakit di kamp-kamp pengungsian.
Namun di tengah kehancuran itu, para janda Gaza seperti Rifqa dan Manal terus bertahan.
Mereka menggenggam harapan demi anak-anak yang tersisa, sembari menunggu datangnya perdamaian yang suatu hari kelak diharapkan mampu menghidupkan kembali Gaza yang terluka.