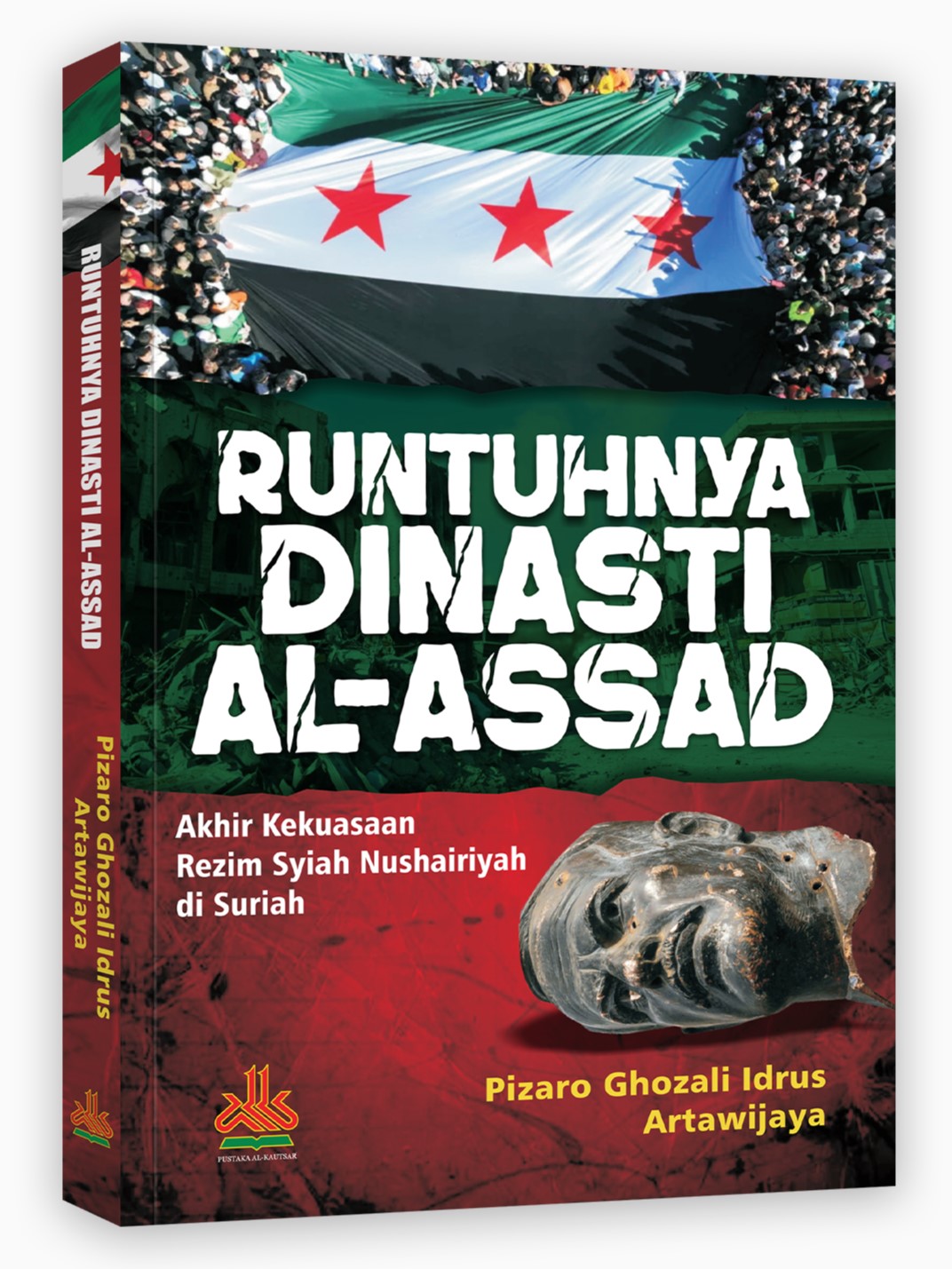Serangkaian penetrasi militer Israel di wilayah selatan Suriah dipandang sebagai upaya untuk memaksakan realitas keamanan baru yang melampaui batas-batas yang selama ini disepakati.
Langkah tersebut berlangsung di tengah dorongan Amerika Serikat (AS) untuk merumuskan pengaturan keamanan yang dapat mencegah eskalasi militer antara Damaskus dan Tel Aviv.
Isu ini dibahas secara mendalam dalam program Skenario, dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang mengupas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang arah hubungan Suriah–Israel ke depan.
Salah satu pertanyaan utama adalah apakah jalur diplomasi mampu menghasilkan kesepakatan keamanan yang benar-benar dapat menghentikan serangan udara dan penetrasi darat Israel.
Atau justru kawasan ini tengah berdiri di ambang eskalasi militer yang lebih luas—sebuah skenario yang berusaha dihindari semua pihak terkait.
Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—yang berstatus buron Mahkamah Pidana Internasional—ke sisi Suriah dari zona penyangga pada 15 November lalu, menunjukkan sejauh mana ambisi Israel menjangkau kedalaman wilayah Suriah.
Langkah tersebut mencerminkan upaya Tel Aviv untuk menguasai kawasan yang melampaui zona penyangga yang telah disepakati sebelumnya.
Israel memanfaatkan kekosongan keamanan pasca runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 untuk memperkuat dan memperluas pendudukannya di wilayah Suriah.
Langkah ini dilakukan dengan melampaui batas-batas Perjanjian Pelepasan Pasukan (Disengagement Agreement) tahun 1974.
Kini, pasukan Israel ditempatkan sepanjang zona penyangga di barat daya Suriah, dengan penguasaan wilayah yang dilaporkan melebihi 400 kilometer persegi.
Dalam beberapa kasus, pasukan Israel bahkan bergerak hingga sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Suriah.
Logika kekuasaan
Penulis dan peneliti politik Suriah, Mudhar al-Debs, menilai bahwa perilaku Israel sejatinya konsisten sejak berdirinya negara tersebut.
Menurut dia, Israel bertindak dengan “logika geng”, meskipun meminjam instrumen-instrumen kenegaraan.
Ia menjelaskan bahwa Perjanjian 1974 selama ini selalu menjadi rujukan dalam berbagai proses negosiasi.
Namun, Israel kini dinilai telah sepenuhnya meruntuhkan kesepakatan itu dan menempatkan kawasan dalam situasi yang “rapuh seperti berdiri di atas pasir”.
Dari sisi kemanusiaan, peneliti hubungan internasional Bassam Sulaiman menekankan bahwa pertanyaan paling mendesak adalah sejauh mana masyarakat Suriah di wilayah-wilayah yang dimasuki Israel mampu bertahan.
Ia menyebut bahwa penderitaan nyata dan rasa terhina akibat pelanggaran-pelanggaran Israel telah mendorong sebagian warga Suriah untuk melakukan perlawanan.
Sebagaimana terjadi di Kota Beit Jin, di mana sedikitnya 13 warga Suriah tewas akibat tembakan pasukan pendudukan.
Sementara itu, akademisi dan pakar urusan Israel, Dr. Muhannad Mustafa, menegaskan bahwa Israel memperlakukan wilayah Suriah sebagai tanah pendudukan yang berada sepenuhnya di bawah kedaulatannya.
Ia menilai logika kolonial dan pendudukan Israel bersifat konsisten—apa yang dilakukan di Tepi Barat, juga diterapkan di Suriah, Lebanon, dan Gaza.
Menurut Mustafa, Israel hingga kini belum sepenuhnya memahami karakter sistem politik Suriah yang baru dan masih meragukan arah kebijakannya, terutama setelah peristiwa 7 Oktober yang mengubah cara Israel memandang seluruh kawasan.
Ia menambahkan bahwa Israel berupaya memengaruhi masa depan Suriah dan orientasi rezim barunya, dengan keyakinan bahwa penguasaan wilayah dan kontrol atas penduduk adalah sarana paling efektif.
Ancaman fragmentasi Suriah
Dalam konteks yang sama, peneliti Pusat Timur Tengah di Brookings Institution, Dr. Steven Heydemann, menyatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyadari bahwa pendudukan Israel atas wilayah Suriah bertentangan dengan tujuan Washington untuk mendukung stabilitas Suriah.
Heydemann memperingatkan bahwa langkah Israel berpotensi memecah Suriah dan menciptakan ruang bagi munculnya gerakan separatis, khususnya di kalangan komunitas Druze di wilayah selatan.
Ia mengajukan pertanyaan krusial: sejauh mana pemerintahan Trump bersedia menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar terlibat secara serius dalam perundingan yang dapat menghasilkan kesepakatan keamanan berbasis garis pemisahan pasukan tahun 1974.
Menurut Heydemann, kunjungan Netanyahu ke Washington dalam waktu dekat akan menjadi momen penentu dalam hal ini.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa secara diplomatik, AS akan menghadapi kesulitan besar untuk benar-benar mencegah Israel melakukan operasi militer.
Washington, kata Heydemann, telah menyatakan kesediaannya menerima tindakan Israel jika Tel Aviv menilai ada ancaman keamanan langsung dari Suriah selatan.
“Di sinilah letak masalahnya, karena Israel menafsirkan posisi ini dengan cakupan seluas mungkin,” ujarnya.
Mudhar al-Debs juga menyoroti Undang-Undang Referendum Israel yang disahkan pada 2010 dan diamendemen pada 2014.
Aturan tersebut melarang Israel menarik diri dari wilayah pendudukan mana pun tanpa persetujuan sedikitnya 80 anggota Knesset—sekitar 70 persen dari total anggota parlemen—sebuah syarat yang nyaris mustahil dipenuhi.
Ia menegaskan bahwa praktik “premanisme” Israel justru dilandasi oleh hukum dasar yang memiliki kedudukan setara dengan konstitusi.
Al-Debs menekankan pentingnya tidak semata-mata menggantungkan harapan pada AS.
Ia menyerukan pembentukan sikap Arab yang bersatu untuk menghadapi Israel.
Ia juga mencatat bahwa Israel saat ini—di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu serta dua menteri sayap kanan ekstrem, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich—sangat berbeda dari Israel yang pernah dikenal kawasan sebelumnya.
Bassam Sulaiman menambahkan bahwa keuntungan terbesar bagi Tel Aviv justru terletak pada absennya persatuan nasional Suriah.
Menurut dia, Israel dengan mudah mengeksploitasi perpecahan internal dan berinvestasi pada kelompok atau komunitas tertentu, menjadikannya titik lemah yang dapat dimasuki kapan saja.
Sulaiman menjelaskan bahwa negara Suriah kini berupaya mengumpulkan modal kekuatan dan tekanan melalui diplomasi aktif dengan dunia Arab, Turki, bahkan Rusia.
Dalam setiap perundingan, Damaskus disebut bersikap tegas dengan menuntut adanya jadwal waktu yang jelas bagi penarikan pasukan Israel dari wilayah yang dimasuki setelah 8 Desember 2024 sebagai prasyarat utama bagi kesepakatan keamanan apa pun.
Mengenai kemungkinan skenario ke depan, Mudhar al-Debs menilai kesepakatan keamanan tetap mungkin tercapai.
Namun, ia mencatat adanya keinginan Israel untuk menundanya selama mungkin, terutama karena pertimbangan politik domestik dan posisi Netanyahu.
Ia memperingatkan bahwa penundaan berkepanjangan justru dapat memicu ledakan situasi yang pada akhirnya menggagalkan peluang tercapainya kesepakatan tersebut.