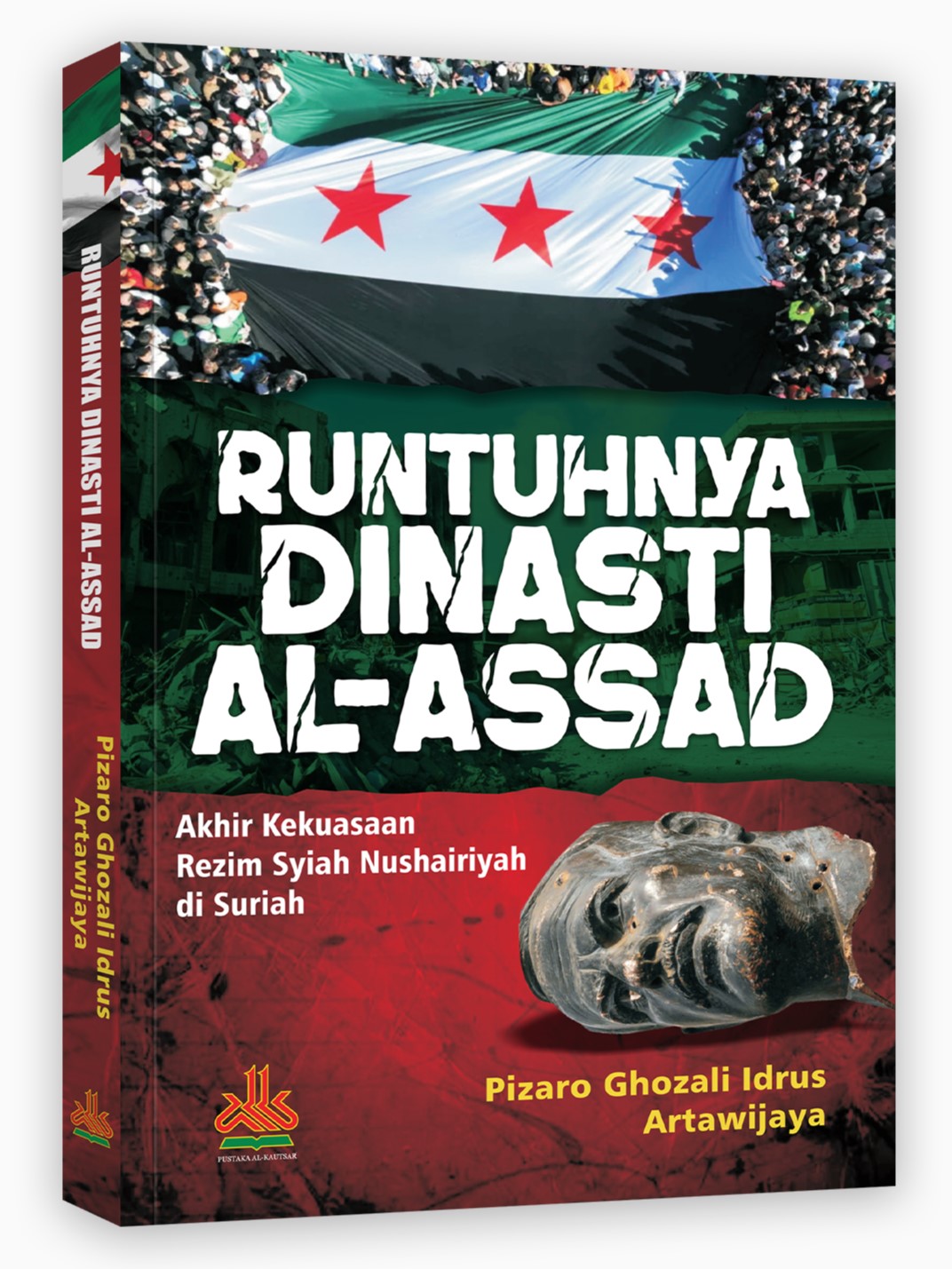Sejumlah analis menilai bahwa proses transisi menuju tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza menghadapi hambatan politik dan keamanan yang serius.
Hambatan tersebut muncul di tengah terus berlanjutnya pelanggaran Israel terhadap kesepakatan.
Selain itu juga perbedaan pandangan internasional mengenai pembentukan pasukan stabilisasi internasional dan rencana pembentukan pemerintahan teknokrat yang akan mengelola Gaza pada fase berikutnya.
Douglas Bandow, peneliti senior di Cato Institute sekaligus mantan asisten khusus Presiden Amerika Serikat (AS), Ronald Reagan, mengatakan bahwa tantangan utama dalam penerapan tahap kedua adalah ketiadaan gencatan senjata yang sesungguhnya.
Dalam wawancaranya dengan program Al-Masa’iya di Al Jazeera Mubasher, Jumat malam, Bandow menegaskan bahwa pelanggaran yang terus dilakukan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata membuat setiap kemajuan politik menjadi amat sulit.
Bandow menambahkan, Washington dihadapkan pada sejumlah persoalan krusial, terutama tuntutan pelucutan senjata terhadap Hamas, yang secara tegas ditolak oleh kelompok tersebut sebagai prasyarat untuk memasuki tahap kedua.
Selain itu, terdapat pula perbedaan tajam mengenai pembentukan pasukan penjaga stabilitas, terutama menyangkut penolakan Israel terhadap keterlibatan Turki.
Selain itu juga keinginan Tel Aviv agar pasukan tersebut tidak diberi mandat apa pun terkait pelucutan senjata.
Ia juga mengkritik berlanjutnya operasi militer Israel dan kebijakan penutupan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Menurut Bandow, kondisi tersebut sepenuhnya bertentangan dengan wacana perdamaian maupun rencana pembentukan pemerintahan teknokrat.
Ia menegaskan bahwa anak-anak di Gaza terus menjadi korban—meninggal akibat pemboman, cuaca dingin, serta terhambatnya bantuan kemanusiaan.
Terkait peran AS, Bandow menilai pemerintahan Presiden Donald Trump sejauh ini belum memberikan tekanan nyata terhadap pemerintah Israel.
Washington, menurutnya, tidak menunjukkan ancaman sanksi apa pun meskipun pelanggaran terus terjadi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengakuan jujur dari AS bahwa Israel merupakan pihak yang menghambat pelaksanaan kesepakatan melalui kelanjutan serangan militer.
Tiga Isu Penentu
Dalam analisisnya mengenai prospek tahap kedua, Ibrahim Al-Khatib, profesor manajemen konflik internasional di Doha Institute, menyebut bahwa perundingan yang tengah berlangsung di Miami harus mampu menyelesaikan tiga isu mendasar.
Isu pertama adalah sifat dan kewenangan pasukan stabilisasi internasional, agar tidak berubah menjadi bentuk pendudukan baru, melainkan terbatas pada tugas menjaga ketenangan dan stabilitas di Gaza.
Isu kedua, lanjut Al-Khatib, berkaitan dengan komposisi pasukan tersebut, terutama menyangkut keberatan Israel terhadap keikutsertaan Turki.
Masalah ini, menurutnya, harus diselesaikan melalui konsultasi antara Washington dan para mediator regional, khususnya Qatar, Mesir, dan Turki.
Adapun isu ketiga menyangkut kerangka waktu rekonstruksi Gaza, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta penetapan tenggat yang jelas untuk penerapan tahap kedua perjanjian.
Al-Khatib menekankan bahwa faktor penentu tetap terletak pada sejauh mana pemerintahan Trump bersedia menekan Israel.
Ia menilai Tel Aviv berupaya memaksakan pelucutan senjata Hamas tanpa memberikan konsesi apa pun terkait penarikan pasukan militernya, meskipun rencana Trump secara eksplisit mencantumkan penarikan bertahap Israel seiring dimulainya tahap kedua.
Ia juga menyoroti bahwa berlanjutnya serangan udara dan tembakan artileri Israel, meski kesepakatan telah berlaku, mencerminkan upaya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional—untuk menciptakan fakta baru di lapangan.
Menurut Al-Khatib, kegagalan AS membendung pelanggaran tersebut berisiko mengarah pada dua kemungkinan: kembalinya perang terbuka atau terbentuknya situasi keamanan yang rapuh dan berkepanjangan.
Rencana pemerintahan teknorat
Sementara itu, Hussein Haridy, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Mesir, menjelaskan bahwa sebelumnya telah tercapai kesepahaman awal.
Kesepakatan itu antara faksi-faksi Palestina dan Otoritas Palestina mengenai pembentukan komite teknokrat—atau komite pendukung masyarakat—yang terdiri atas 10 tokoh independen tanpa afiliasi faksional untuk mengelola masa transisi.
Ia menegaskan tidak mengetahui adanya pembatalan resmi atas kesepakatan tersebut.
Terkait pasukan stabilisasi internasional, Haridy menyebut bahwa mandat pasukan itu telah diatur dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada Oktober lalu dan menjadi lampiran dari rencana Presiden AS.
Namun, ia mengakui adanya sejumlah catatan dan keberatan dari Mesir, Qatar, dan Turki mengenai mekanisme pembentukan dan komposisi pasukan tersebut, yang hingga kini masih menjadi bahan konsultasi.
Penolakan terhadap keterlibatan Turki
Dalam konteks yang sama, analis militer asal Turki, Yusuf Al-Abarda, menilai penolakan Israel terhadap partisipasi Turki dalam pasukan stabilisasi tidak memiliki dasar hukum maupun legitimasi politik.
Ia menegaskan bahwa Gaza bukanlah wilayah Israel, sehingga Tel Aviv tidak berhak menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional.
Menurut Al-Abarda, Israel berupaya menggagalkan tahap kedua karena kehadiran pasukan internasional akan menciptakan mekanisme pengawasan yang mampu mengungkap siapa pihak yang sebenarnya melanggar gencatan senjata.
Ia menilai penundaan pembentukan pasukan stabilisasi bertujuan untuk mengulur waktu sekaligus melanjutkan penciptaan fakta-fakta baru di lapangan.
Pada akhir diskusi, para narasumber sepakat bahwa keberhasilan tahap kedua perjanjian Gaza sangat bergantung pada penyelesaian sejumlah isu krusial.
Yaitu, penarikan pasukan Israel, karakter dan mandat pasukan stabilisasi internasional, bentuk pemerintahan sipil di Gaza, serta tersedianya jaminan nyata bagi gencatan senjata yang berkelanjutan.
Mereka memperingatkan bahwa kegagalan mengatasi persoalan-persoalan tersebut berpotensi menyeret Gaza kembali ke siklus eskalasi kekerasan atau mengukuhkan kondisi ketidakstabilan jangka panjang.